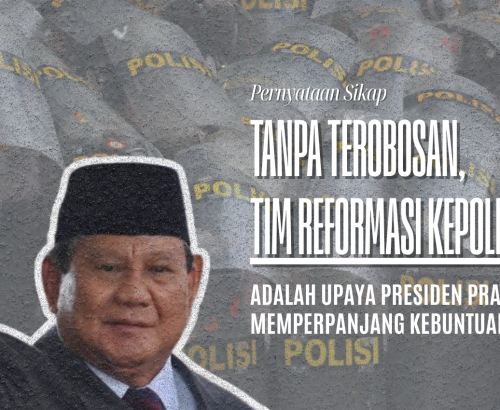Bagikan Artikel
- Senandika
-
Kita Semua (Bisa Jadi) Prekariat
Kita Semua (Bisa Jadi) Prekariat
Blog | 16 Okt 2025Setiap pekerja pasti ingin punya rasa aman. Kalau sakit, kita tidak perlu takut berobat karena ada BPJS Kesehatan atau asuransi yang menanggung biayanya. Jika mengalami kecelakaan kerja, ada perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Punya hak cuti, libur, tunjangan, bahkan kepastian pensiun. Hal-hal yang dulu dianggap standar ini, kini justru terasa semakin langka.
Kenyataannya, banyak pekerja yang saat ini hidup dalam ketidakpastian. Kontrak semakin pendek, jam kerja fleksibel tapi tak jelas, dan perlindungan sosial seringkali tak ada. Fleksibilitas yang dijanjikan kerap berakhir menjadi ketidakpastian yang membebani.
Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia memang tengah menghadapi tantangan serius. Laporan East Asia and Pacific Economic Update October 2025 dari Bank Dunia menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara di Asia Timur dan Pasifik dengan lonjakan pekerja informal di sektor jasa tertinggi, sehingga banyak pekerja kehilangan kepastian kerja, penghasilan tetap, dan perlindungan sosial. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren serupa: dominasi pekerja informal di Indonesia terus meningkat tiap tahunnya. Per Februari 2025, jumlah tenaga kerja informal mencapai 86,56 juta orang atau sekitar 59,40% dari total penduduk yang bekerja.
Fenomena ini kerap disebut sebagai prekariatisasi—suatu kondisi di mana semakin banyak pekerja berada dalam situasi kerja yang tidak stabil dan tanpa jaminan. Dari pilot dan pramugari di industri penerbangan sampai ojek online yang setiap hari menghadapi risiko kerja, batas antara stabilitas dan kerentanan yang dihadapi pekerja menjadi semakin tipis. Dampaknya bukan hanya finansial: tekanan mental, stres, dan rasa terisolasi membuat mereka kerap menyalahkan diri sendiri, alih-alih menyadari bahwa masalah ini bersifat struktural.
Untuk memahami lebih jauh konsep prekariat dan dinamika di baliknya, Kurawal berbincang dengan Diatyka Widya Permata Yasih, akademisi dari Universitas Indonesia, dan Syarif Arifin, Direktur Eksekutif Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS). Dalam wawancara ini, keduanya mengupas bagaimana prekariatisasi bisa merebak, tantangan yang dihadapi pekerja, dan cara membangun solidaritas.
***
Apa yang dimaksud dengan prekariat?
Diatyka: Prekariat itu dalam literatur berarti orang-orang yang kondisi kerjanya rentan, ditandai oleh ketidakamanan, ketidakstabilan, ketidakpastian kerja. Tidak ada pensiun, pendapatan tetap, hari libur kadang-kadang, upah minimum, atau kontrak kerja. Rentangnya sangat luas. Kondisi ini terjadi karena risiko yang semula ditanggung negara dan perusahaan kini dialihkan ke pekerja.
Konsep prekariat sendiri muncul dan menjadi besar karena mulai bangkrutnya negara kesejahteraan di Eropa Barat dan Amerika Utara. Kalau di Global North, dulu ada asuransi bagi yang tidak bekerja, meskipun perlindungannya singkat. Namun sejak pasca Perang Dunia sampai 1970-an, sistem itu mulai drop. Salah satu dampaknya adalah fleksibilisasi pasar tengara kerja. Jadi semakin banyak orang yang dipekerjakan secara enggak tetap.
Aku sendiri lebih suka menggunakan istilah prekariatisasi, kondisi dimana semakin banyak orang yang bekerja dalam bentuk yang rentan, dalam sektor apapun. Di Indonesia, sebelum krisis moneter, (kerja) di sektor formal dibilang relatif aman. Ada tunjangan segala macam. Sekarang, orang masuk sektor formal juga bisa jadi cuma kontrak. PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) makin banyak. Honorer makin banyak, dan itu ada di semua sektor.
Artinya, prekariatisasi tidak hanya dialami oleh pekerja informal? Pekerja formal juga mengalaminya?
Diatyka: Ya, pekerja formal juga mengalami kasualisasi. Di pabrik, banyak outsourcing bentuknya. Di pemerintahan, ada berbagai jenis PK (perjanjian kerja) seperti PKWT, PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu), dan PK lainnya. Setiap rezim punya istilah sendiri, tapi intinya sama—statusnya sementara.
Kalau dari pengalaman di lapangan, bentuk kerja yang paling tidak aman itu seperti apa?
Syarif: Maksudnya jenis pekerjaan yang memberikan ketidakpastian kerja?
Pertama, dari karakter industrinya. Ada yang karakternya memang berbahaya, misalnya pertambangan. (Di sana) orang bisa meninggal karena sesak napas atau sakit akibat bekerja. Selain faktor bahaya dalam cara kerja, ada pula bentuk ketidakamanan yang muncul dari jenis industrinya.
Penerbangan adalah salah satu sektor industri yang tidak aman dari segi karakter industri maupun dari cara kerja. Industri bandara bergantung kepada sektor-sektor lain, seperti industri pariwisata, manufaktur, dan lainnya. Tanpa adanya sektor lain, industri bandara tidak bisa hidup.
Gabungan antara sektor yang tidak pasti dan jenis kerjanya yang berbahaya bisa ditemukan di ojol (ojek online).
Aspek ketiga dari ketidakamanan adalah relasi kerja. Sekarang orang mudah ”dibuang” kapanpun. Pola hubungan kerja yang fleksibel justru telah menjadi kebijakan umum di tingkat perusahaan maupun negara. Sekarang kita mengenal sistem kontrak, yang durasinya makin pendek. Tiga puluh atau 40 tahun lalu, model kerja seperti ini bisa jadi tidak ada. Dulu, pekerjaan idaman seperti BUMN dan PNS menawarkan status tetap, bahkan kerja di pabrik pun begitu. Kalau sekarang, semuanya kontrak.
Semakin banyak orang kehilangan kepastian, ya? Terlepas dari urusan dompet, dampak jangka panjangnya seperti apa bagi pekerja?
Diatyka: Itu yang tadi aku bilang, sektor formal juga mengalami kasualisasi. Informalisasi. Formal juga punya karakter informal.
Kalau individual (dampaknya) kan stres, mental health, segala macam. Tapi menurutku, dampak utamanya adalah individualisasi risiko. Kita jadi self-blamimg. Misalnya, di kampus, banyak yang berpikir: ”Gue harus kerja sekeras-kerasnya buat survive.” Akibatnya, orang enggak tahu dan kenal bahasa solidaritas atau pengorganisasian karena sibuk bertahan sendiri.
Yang perlu dikhawatirkan, selain makin banya orang ngerasa capek, kita jadi sendiri-sendiri. Kita enggak tahu kalau orang di sekitar kita juga prekariat. Walaupun mungkin hidupnya terlihat mentereng atau happy, bisa jadi mereka juga rentan.
Dampaknya, kita memandang situasi ini sebagai kesalahan pribadi, bukan masalah struktural. ”Ini salah gue, temen gue lebih pintar, atau orang tuanya lebih kaya.” Akhirnya, kita enggak ngomong solidaritas lagi—dan ini masih di dalam sektor. Bagaimana kalau lintas sektor?

Semakin ke sini, apakah garis pembeda antara buruh dan prekariat bisa dibilang hilang?
Diatyka: Kalau bicara buruh, definisinya adalah orang yang enggak punya alat produksi dan bekerja untuk mendapatkan gaji. Jadi, buruh bukan cuma pekerja pabrik, tapi semua yang enggak punya alat produksi kemudian punya gaji. Dari definisi itu sendiri aja, agak kurang tepat bilang buruh versus prekariat. Ke pertanyaan tadi, menurutku semua sektor sekarang mengalami prekariatisasi, hanya dampaknya beda-beda.
Bicara soal individualisasi, seberapa sulit mengorganisir pekerja, baik prekariat maupun bukan? Secara realistis, bisa mulai dari mana?
Diatyka: Mulai (mengorganisir) dari titik-titik lemah dalam semua rantai produksi, (lalu) mengumpulkannya. Meski belum tahu ujungnya ke mana karena secara literatur belum ketemu strateginya. Intinya, bangun solidaritas di tempat masing-masing dan sadari bahwa kondisi struktural lah yang membuat kita terfragmentasi. Jadi, sebisa mungkin jangan berantem sama temen sendiri. Kalau marah, marahlah ke atas (pemerintah dan pemilik modal) dan kalau bisa bersama-sama.
Syarif: Dibanding sepuluh tahun lalu, situasi sekarang lebih bagus. Narasi perburuhan lebih hidup. meski penderitaannya lebih banyak, ya. Sepuluh tahun lalu, mencari tulisan soal perburuhan susahnya bukan main. Sekarang, skripsi-skripsi banyak membahas isu ini. Dari aspek narasi memang membaik, meski gerakan buruhnya melemah. Sepuluh tahun lalu, gerakan buruhnya memang lagi bagus. Aksi buruh banyak di mana-mana, pendidikan jalan, media aktif, keanggotaan serikat tinggi. Tapi narasinya lemah.
Menurutku, sekarang (dibutuhkan) bentuk perlawan yang lebih muda dan segar. Serikat buruh yang sekarang barang kali sudah terlalu konvensional bentuk-bentuk perlawanannya. Sekarang ada serikat buruh yang lebih muda seperti Serikat Pekerja Kampus dan Sindikasi.
Kenapa penting mencatat dan mengenali titik-titik perlawanan, sekecil apa pun itu?
Diatyka: Menurutku, titik perlawanan di mana pun perlu ditangkap dan diidentifikasi.
Syarif: Benar. Misalnya ada satu keberhasilan kecil di Banten, menuntut BPJS Kesehatan gratis untuk pengemudi ojek online. Biasanya, program itu gratis hanya untuk orang miskin yang didaftarkan oleh RT/RW, tapi berhasil memaksakan kebijakan baru. Itu contoh keberhasilan kecil yang bisa direplikasi.
Selain itu, ada aksi-aksi yang mengerahkan massa lebih banyak, seperti aksi Agustus-September, sampai Tolak RUU TNI. Semua menandakan bahwa perlawanan tetap ada. Yang penting, menangkap dan mendokumentasikannya. Sekarang bukan lagi soal mereplikasi penderitaan, tapi mereplikasi perlawanan.
Pekerjaan yang dulu diidamkan, sebagai ASN, dosen, atau pegawai BUMN, sekarang makin rentan. Karena itu, penting merekam bentuk-bentuk perlawanan baru.
Diatyka: Tapi perlu diingat, dalam perlawanan, selalu ada kontradiksi. Kadang komunitas yang saling bantu bisa jadi mengiyakan penindasan. Jadi, penting mencatat dengan jeli. Jangan sampai solidaritas berubah jadi bentuk pasrah kolektif: ”Gak apa-apa tertindas asal rame-rame.” Terus jadinya menindas orang yang ada di bawah kita.
Dalam kondisi ideal, perubahan apa yang kita butuhkan untuk keluar dari bangsa prekariat?
Diatyka: Jujur, aku enggak tahu perubahan yang kayak apa. Kalau secara literatur, prekariat muncul setelah negara kesejahteraan runtuh. Tapi sejarah kita berbeda. Apakah kita bisa membangun negara kesejahteraan di Indonesia? Belum tentu.
Mungkin yang kita butuhkan sekarang sebuah situasi di mana kelas pekerja punya kapasitas untuk bernegosiasi secara setara. Punya kekuatan untuk bernegosiasi dengan negara dan kapital, ya. Bukan sekadar diberi konsesi, tapi punya kapasitas bernegosiasi. Untuk itu, kelas pekerjanya sendiri harus lebih demokratis, karena saat ini masih ada gap antara elit gerakan buruh dan massa buruhnya.
***
Entah sadar atau tidak, kita semua bisa jadi prekariat. Di balik jargon “fleksibilitas” dan “kebebasan kerja”, banyak dari kita hidup di bawah bayang-bayang ketidakpastian yang sama: takut kehilangan penghasilan, cemas soal jaminan kesehatan, bingung ke mana mencari perlindungan ketika mengalami kecelakaan kerja. Tapi seperti kata Diatyka dan Syarif, masalah ini ada bukan karena kita, sebagai pekerja, kurang berusaha atau salah memilih jalan hidup. Ini soal struktur yang membuat kita mudah digantikan, mudah dipecah, dan sulit bersuara. Dan mungkin, titik baliknya bukan datang dari solusi besar atau kebijakan instan, melainkan dari keberanian untuk saling melihat dan membangun solidaritas—di kampus, di pabrik, di jalanan, atau bahkan di layar-layar gawai kita. Karena di tengah sistem yang membuat kita terasing satu sama lain, mengenali bahwa penderitaan kita serupa bisa jadi langkah pertama untuk melawan.