Bagikan Artikel
- Publikasi
-
Menimbang Rimpang: Unpacking Civil Society in Post-Authoritarian Indonesia
Menimbang Rimpang: Unpacking Civil Society in Post-Authoritarian Indonesia
Penelitian | 08 Jul 2025Ada yang sedang tumbuh dan menjalar pelan-pelan dalam ekosistem masyarakat sipil di Indonesia hari ini: gerakan rimpang. Mereka tak berbentuk institusi, tak punya kantor, bahkan kadang tak punya nama. Mereka hidup melalui obrolan komunitas, kolektif seni, forum dadakan, atau sekadar postingan viral yang bikin banyak orang tergerak.
Kebanyakan gerakan macam ini dimotori oleh orang muda yang muncul bukan karena disuruh senior abang-abangan dan bukan karena digerojoki cuan. Mereka hadir karena ada keresahan, bangkit karena ada ketidakadilan yang ingin dilawan. Rimpang bergerak dengan cara mereka sendiri: cepat, lentur, dan penuh intuisi.
Riset “Unpacking Civil Society in Post-Authoritarian Indonesia” oleh Asia Research Center, Universitas Indonesia (ARC UI) dan Research Centre for Politics and Government, Universitas Gadjah Mada (PolGov UGM) menyebut ini bukan sebuah kebetulan. Gerakan rimpang lahir dari dunia yang makin tidak pasti. Di satu sisi, represi (negara) makin canggih. Di sisi lain, hidup warga terasa makin sulit. Di tengah dua tekanan ini, gerakan rimpang justru menunjukkan daya hidupnya. Mereka adaptif, peka terhadap isu, dan bisa bikin gelombang politik dari ruang-ruang yang kecil, bahkan dari tempat yang sebelumnya tak dianggap "politis".
Walau begitu, gerakan ini juga ada batasnya. Banyak dari mereka bergerak dari kekurangan: minim dana, waktu, tenaga, dan ruang aman. Mereka bukan pemain besar, bukan lembaga advokasi, maupun organisasi yang duduk di meja kebijakan. Maka tidak adil rasanya kalau mereka dituntut untuk selalu "berdampak", "berkelanjutan", atau "terukur". Mereka sudah melakukan banyak, meski dengan sedikit.
Masalahnya bukan di rimpangnya.
Organisasi masyarakat sipil dan lembaga donor, yang semestinya bisa jadi "pohon" penopang gerakan, masih sering terjebak dalam logika proyek: terlalu struktural, terlalu teknokratis. Banyak yang menuntut gerakan harus bisa direncanakan, dimonitor, dievaluasi. Lalu lupa, bahwa tidak semua bentuk perlawanan bisa masuk ke kotak-kotak itu. Gerakan rimpang bukan versi mentah dari institusi. Mereka sah sebagai bentuk gerakan. Hanya saja, bentuknya memang berbeda.
Dan di sinilah kita butuh sesuatu yang sering terlupa: pohon perdu. Pohon perdu adalah metafora untuk mereka yang bisa menjembatani: antara gerakan yang menjalar dan struktur yang mengakar. Mereka lah yang bisa menerjemahkan keresahan jadi strategi menyambungkan gerakan jalanan dengan ruang kebijakan, menyatukan energi kolektif dengan arah perubahan yang lebih luas.
Sayangnya, peran ini masih jarang. Akibatnya, banyak gerakan yang hebat tapi cepat padam. Banyak inisiatif yang menyala sebentar, lalu tak tahu ke mana harus melangkah. Dan banyak organisasi besar yang berjalan sendiri, kehilangan koneksi dengan denyut akar rumput.
Yang dibutuhkan bukan rimpang yang berubah jadi pohon. Tapi pohon yang cabangnya lentur, yang akarnya kuat tapi tak kaku. Yang tahu bahwa mendukung gerakan tidak harus berarti mengatur. Karena akar yang kuat saja tak cukup jika tak bisa merambat ke luasnya tanah.
Riset ini memberi pengingat penting: gerakan bukan soal siapa yang paling besar atau paling rapi. Tapi soal bagaimana kita membangun ekosistem yang saling menguatkan. Kalau kita ingin perubahan yang benar-benar berakar, maka kita perlu jembatan. Kita perlu pohon perdu yang mau mendengar, menyambung, dan merawat jejaring gerakan hari ini.
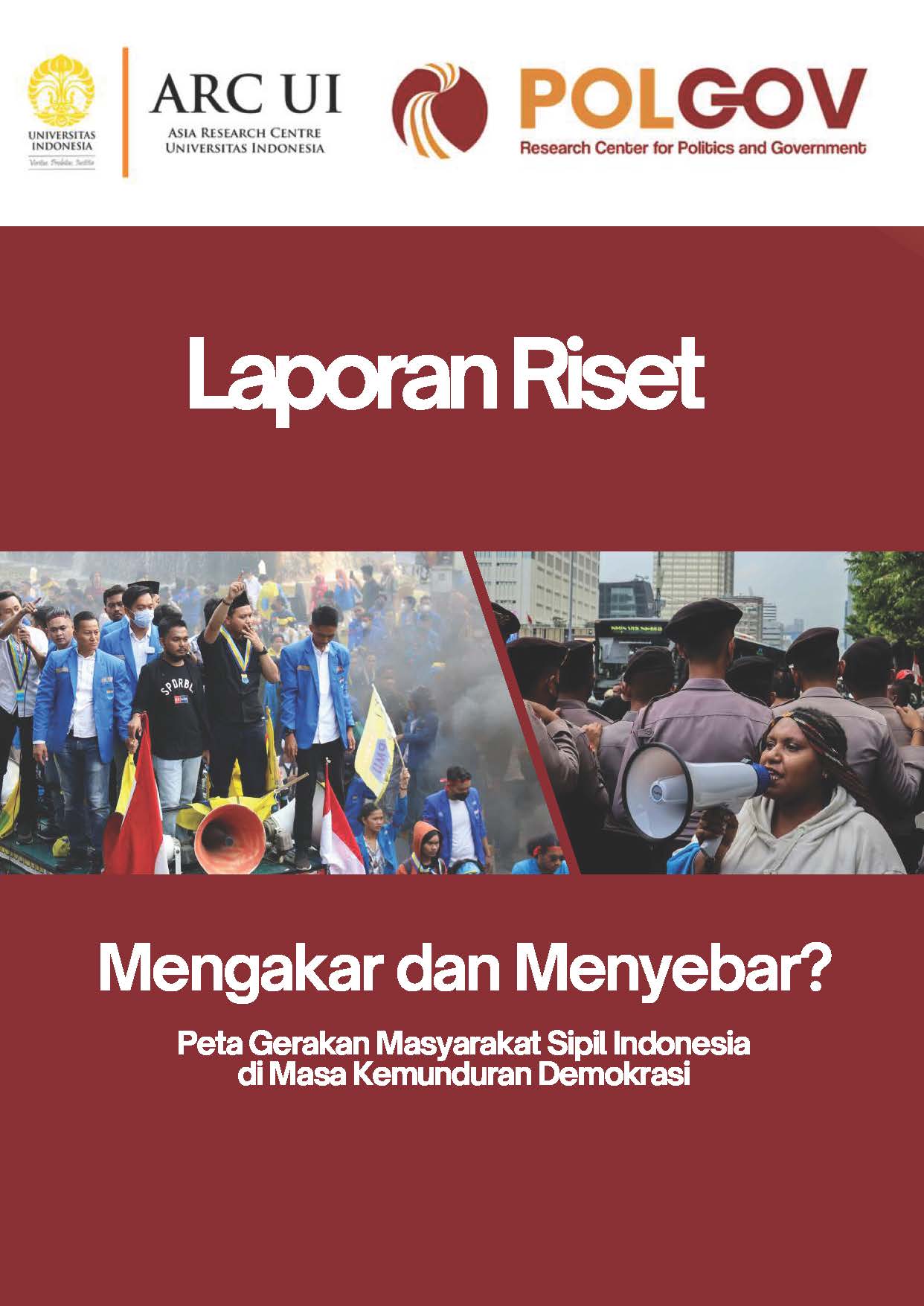
| Judul | : | Mengakar dan Menyebar? Peta Gerakan Masyarakat Sipil Indonesia di Masa Kemunduran Demokrasi |
| Peneliti | : | Amalinda Savirani, Diatyka Widya Permata Yasih, Inaya Rakhmani, Suryani, Firdasari, Rose, Dwi Aini Bestari |
| Penerbit | : | Asia Research Centre, Universitas Indonesia (ARC UI), Research Centre for Politics and Government, Universitas Gadjah Mada (POLGOV UGM) |
| Jumlah Halaman | : | 28 halaman |
| Tahun Terbit | : | 2025 |
| Bahasa | : | Indonesia |